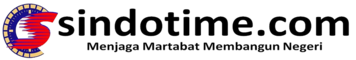Oleh: MUHAMAD AKBAR
DI sebuah persimpangan padat di Jakarta, seorang pengendara
dengan buta warna parsial terhenti sejenak. Dari kejauhan, lampu lalu lintas
tampak menyala terang, namun ia diliputi keraguan: apakah itu merah atau hijau?
Secara umum, posisi lampu memberi petunjuk—lampu di atas berarti merah, lampu
di bawah hijau. Tetapi dalam kondisi nyata di jalan raya, terutama saat malam
hari atau ketika hujan, pantulan cahaya dan keterbatasan jarak pandang kerap
membuat penafsiran menjadi keliru. Ini bukan kisah rekaan. Dengan angka
kejadian buta warna parsial sekitar 5–8 persen pada laki-laki, diperkirakan
lebih dari delapan juta orang di Indonesia menghadapi tantangan serupa setiap
hari di jalan raya.
Perhatian terhadap persoalan ini kini sampai ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Dalam Putusan Nomor 149/PUU-XXIII/2025, majelis hakim memang
menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, putusan itu justru memuat amanat penting. MK
menegaskan bahwa pelaksanaan aturan tersebut harus memperhatikan keselamatan
penyandang disabilitas visual. Wakil Ketua MK Arsul Sani menyatakan, “Termasuk
mereka yang mengalami buta warna parsial, dengan melengkapi sarana dan prasarana
lalu lintas yang melindungi dan memberikan rasa aman bagi mereka semua,
termasuk menyediakan alat pemberi isyarat lalu lintas yang mengakomodasi
kebutuhan penyandang defisiensi penglihatan warna.”
Berikut adalah sejumlah butir kunci dari putusan tersebut:
Fact Box
● Putusan MK Nomor 149/PUU-XXIII/2025
● Perkara: Pengujian Materiil terhadap Pasal 25 ayat (1)
huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
● Pemohon: Singgih Wiryono dan Yosafat Diva Bayu Wisesa
(wartawan penyandang buta warna parsial).
● Pokok Permohonan: Menguji keabsahan sistem lampu lalu
lintas (APILL) yang hanya mengandalkan warna, dinilai diskriminatif dan tidak
menjamin keselamatan bagi penyandang disabilitas visual.
● Amar Putusan: Permohonan ditolak. Materi muatan ayat yang
dimohonkan untuk diuji dinyatakan konstitusional.
● Pertimbangan Penting MK: Meski menolak permohonan, MK
menegaskan bahwa implementasi UU wajib inklusif. Pemerintah harus mengakomodasi
kebutuhan penyandang buta warna dalam kebijakan teknisnya.
● Implikasi Hukum: Putusan ini menjadi landasan hukum yang
kuat bagi pemerintah untuk segera menyusun dan merevisi peraturan teknis,
standar nasional (SNI), serta menata ulang sarana lalu lintas yang aksesibel
bagi semua.
Ketika Lampu Lalu Lintas Tak Bisa Dibaca Semua Mata
Jalan raya adalah ruang publik yang harus aman bagi semua.
Namun, ketika lampu lalu lintas (APILL) hanya mengandalkan kode warna merah,
kuning, dan hijau, penyandang buta warna seakan terpinggirkan dari sistem
keselamatan lalu lintas. Padahal, konstitusi secara jelas menjamin hak setiap
warga negara untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan. Mengabaikan kebutuhan
kelompok ini sama artinya dengan membiarkan sebagian masyarakat menanggung
risiko yang lebih besar di ruang publik yang semestinya setara dan inklusif.
Aksesibilitas di ruang publik bukanlah bentuk kemurahan hati
negara, melainkan hak dasar setiap warga. Lampu lalu lintas yang bisa dipahami
penyandang buta warna harus dipandang sama pentingnya dengan rambu-rambu
keselamatan lainnya yang wajib disediakan bagi seluruh pengguna jalan. Analogi
yang sederhana dapat menjelaskan hal ini: pembangunan ramp bagi kursi roda di
sebuah gedung bukanlah fasilitas tambahan, melainkan syarat agar penyandang
disabilitas dapat masuk dan beraktivitas. Demikian pula, lampu lalu lintas yang
dapat “dibaca” oleh difabel visual adalah prasyarat agar mereka bisa
berpartisipasi dengan aman di jalan raya.
Ketika hak dasar itu diabaikan, dampaknya terasa nyata dalam
kehidupan sehari-hari. Banyak penyandang buta warna merasa khawatir salah
membaca isyarat lampu lalu lintas. Kekhawatiran itu membuat sebagian enggan
menyetir, bahkan ragu sekadar menyeberang jalan. Akibatnya, kesempatan mereka
untuk bekerja, belajar, atau bersosialisasi sering kali ikut terhambat. Lebih
jauh, rasa cemas dan tekanan mental yang harus ditanggung setiap kali berada di
jalan raya menjadi bentuk ketidakadilan yang seharusnya bisa dihindari. Jalan
raya mestinya memberi rasa aman bagi semua, bukan menambah beban bagi sebagian
warganya. Untuk memastikan prinsip itu berjalan, diperlukan langkah nyata dari
pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang jelas.
MK Sudah Bicara, Kini Giliran Pemerintah Membuktikan
Putusan Mahkamah Konstitusi memang hanya bersifat
pertimbangan, bukan perintah eksekusi. Namun, arah yang diberikan jelas:
pemerintah perlu memastikan lampu lalu lintas dapat dipahami semua warga,
termasuk penyandang buta warna. Pertimbangan ini cukup kuat untuk dijadikan
dasar revisi aturan teknis. Kementerian Perhubungan, misalnya, dapat
memperbarui spesifikasi lampu lalu lintas melalui Keputusan Menteri. Revisi ini
tidak mengubah warna atau urutan yang berlaku, melainkan menambahkan elemen
bentuk, simbol, atau pola cahaya agar lebih mudah dibedakan.
Langkah teknis tersebut bisa dilakukan tanpa harus mengubah
undang-undang. Pemerintah pusat cukup menetapkan standar baru yang wajib
diikuti daerah. Setelah regulasi diperbarui, kota-kota besar seperti Jakarta,
Surabaya, atau Bandung dapat segera menyiapkan lokasi dan desain uji coba. Agar
efektif, sosialisasi kepada masyarakat mutlak dilakukan, sehingga setiap
pengendara memahami makna tambahan pada lampu lalu lintas yang baru. Tanpa
edukasi publik, inovasi apa pun berisiko menimbulkan kebingungan di jalan.
Dengan langkah-langkah terencana ini, amanat MK tidak berhenti sebagai wacana,
melainkan benar-benar terwujud dalam sistem lalu lintas yang lebih inklusif.
Pertanyaannya, apakah penambahan simbol atau pola cahaya
pada lampu lalu lintas sejalan dengan standar internasional? Di sinilah
Konvensi Wina 1968 tentang Lalu Lintas Jalan relevan untuk dikaji.
Konvensi Wina: Baku, Tapi Tak Membelenggu
Konvensi Wina 1968 tentang Lalu Lintas Jalan telah lama
menjadi rujukan utama harmonisasi aturan lalu lintas bagi banyak negara,
termasuk Indonesia. Perjanjian internasional ini bertujuan memfasilitasi
mobilitas kendaraan antarnegara sekaligus meningkatkan standar keselamatan
jalan. Dalam lampirannya, konvensi menetapkan standar minimum untuk lampu lalu
lintas, yakni penggunaan tiga warna (merah, kuning, dan hijau) dengan tata
letak yang seragam. Untuk pemasangan vertikal, merah harus berada di posisi
paling atas, disusul kuning di tengah, dan hijau di bawah. Sementara dalam
konfigurasi horizontal, merah menempati sisi kiri dan hijau di sisi kanan. Pola
ini dirancang untuk memastikan sinyal tetap mudah dikenali, termasuk oleh
pengemudi yang mengalami kesulitan dalam membedakan warna. Prinsip dasar yang
dianut adalah setiap sinyal harus “clearly visible and
distinct”—jelas terlihat dan mudah dibedakan secara universal.
Meski mengatur warna dan posisi dengan ketat, Konvensi Wina
tidak menutup ruang bagi inovasi. Dokumen ini pada dasarnya menetapkan standar
minimal, sementara negara peserta tetap memiliki keleluasaan menambahkan
penyesuaian sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan utamanya. Pendekatan
melalui pemahaman atas semangat konvensi, yakni keselamatan dan keterbacaan
universal membuka jalan bagi inovasi yang lebih inklusif bagi semua pengguna
jalan.
Praktik di berbagai negara memperlihatkan bagaimana
pendekatan ini diterapkan. Jepang melengkapi lampu hijau dengan panah untuk
menunjukkan arah yang boleh dilalui. Di banyak negara Eropa dan Amerika Utara,
lampu penyeberangan ditambah ikon orang berjalan atau tangan, sementara Inggris
menambahkan sinyal audio. Contoh-contoh ini menegaskan bahwa inovasi seperti
simbol atau pola cahaya tidak bertentangan dengan Konvensi Wina, melainkan
memperkuat tujuannya: menjadikan lalu lintas lebih aman dan inklusif.
Tantangannya kini bagi Indonesia adalah menerjemahkan ruang inovasi tersebut ke
dalam solusi teknis yang nyata dan dapat segera diterapkan di lapangan.
Bentuk, Simbol, dan Suara: Bahasa Baru Lampu Lalu Lintas
Prinsip dasar yang perlu dipegang adalah redundansi
informasi, yakni menghadirkan lebih dari satu isyarat untuk menyampaikan pesan
yang sama. Dengan cara ini, apabila satu lapisan informasi (misalnya warna)
tidak dapat terdeteksi, lapisan lainnya (seperti bentuk atau simbol) tetap
dapat menyampaikan pesan dengan jelas. Analogi sederhana bisa dilihat pada
rambu Stop berbentuk segi delapan dengan tulisan “STOP”. Bahkan tanpa membaca
tulisannya, bentuk segi delapan itu sudah cukup dikenali pengemudi. Prinsip serupa
dapat diterapkan pada lampu lalu lintas dengan menambahkan bentuk, simbol, atau
pola cahaya di samping warna.
Berbagai solusi teknis dapat diterapkan untuk membuat lampu
lalu lintas lebih inklusif. Lampu merah, misalnya, bisa ditampilkan dalam bentuk
segiempat atau diberi simbol “X” di dalamnya—sebuah tanda universal yang
berarti “berhenti”. Lampu kuning dapat dilengkapi ikon segitiga ⚠️sebagai penanda peringatan atau dibuat berkedip, sementara
lampu hijau diperjelas dengan panah arah ➡️.
Untuk penyeberangan pejalan kaki, ikon orang berjalan atau tangan terbuka untuk
“berhenti” sudah lazim digunakan di berbagai negara. Di titik
penyeberangan, tambahan berupa sinyal audio atau getaran pada tombol akan
sangat membantu pengguna jalan yang kesulitan membaca warna.
Perkembangan teknologi LED menjadi angin segar bagi
terwujudnya lampu lalu lintas yang inklusif. Perangkat modern memungkinkan
berbagai bentuk, simbol, dan pola cahaya yang rumit diprogram dalam satu unit
panel yang sama dengan biaya relatif efisien. Dengan dukungan teknologi ini,
gagasan lampu lalu lintas ramah difabel bukan lagi sebatas wacana, melainkan
solusi yang realistis untuk segera diwujudkan.
Buta Warna Menunggu Lampu Hijau Pemerintah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-XXIII/2025
bukanlah akhir perkara, melainkan justru menjadi ujian nyata bagi komitmen
pemerintah dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negaranya. Negara
diingatkan untuk tidak lagi abai terhadap kebutuhan kelompok penyandang
disabilitas visual, sekecil apa pun itu. Konstitusi sudah jelas menjamin setiap
warga berhak atas rasa aman dan perlindungan, termasuk di jalan raya.
Pertanyaannya kini, apakah pemerintah benar-benar siap untuk menindaklanjuti
putusan tersebut dengan kebijakan konkret, atau membiarkannya sekadar menjadi
catatan hukum tanpa makna.
Implikasinya pun jelas. Jika ditindaklanjuti, Indonesia akan
melangkah maju menuju sistem transportasi yang ramah bagi semua dan beradab.
Namun jika diabaikan, janji kesetaraan hanya berhenti sebagai retorika, sementara
sebagian warga tetap menanggung risiko di jalan raya. Faktanya, seluruh
prasyarat sudah tersedia: ada landasan hukum melalui putusan MK, ada solusi
teknis yang terbukti di banyak negara, dan ada kewenangan penuh Kementerian
Perhubungan untuk memperbarui aturan. Yang dibutuhkan kini hanyalah kemauan
politik (political will) untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Dan kelak, di
simpang jalan yang sibuk itu, seorang pengendara dengan buta warna tak lagi
ragu: ia tahu kapan harus berhenti, dan kapan boleh melaju.(***)