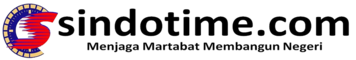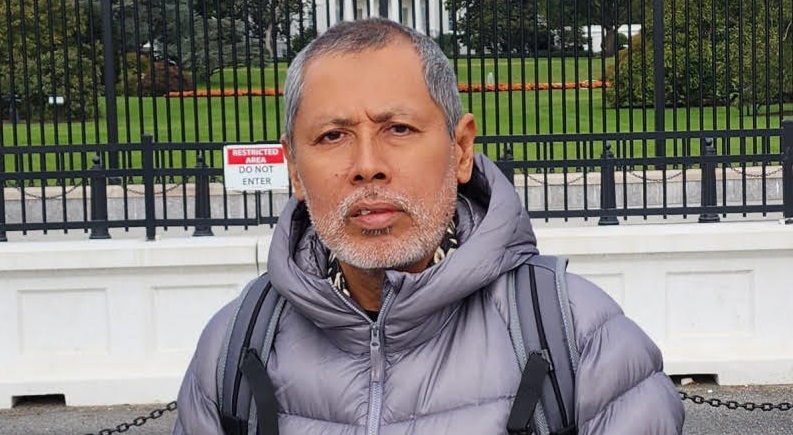Oleh: MUHAMAD AKBAR
PAGI itu, halte yang biasanya riuh dengan penumpang tampak
sepi dan hangus. Sisa-sisa kebakaran masih mengepul dari atapnya yang runtuh.
Bangku-bangku logam hangus terbakar. Poster-poster layanan publik tergantung
setengah terbakar. Di sisi lain jalan, sebuah jembatan penyeberangan penuh
coretan dan serpihan kaca. Situasi lengang, menyisakan jejak kerusakan pasca
demonstrasi yang berlangsung ricuh pada malam sebelumnya.
Jejak Kekerasan di Ruang Publik
Aksi demonstrasi yang berawal di depan Gedung DPR berakhir
ricuh dan meluas ke berbagai wilayah. Sedikitnya enam halte TransJakarta
terbakar dan rusak berat, enam belas halte dirusak termasuk perangkat
elektroniknya, belasan jembatan penyeberangan orang (JPO) dicorat-coret. Kerusakan menjalar hingga Senen,
Tanjung Priok, dan Cawang. Di tengah kobaran api dan pecahan kaca, tersisa
jejak kemarahan yang belum sempat dimaknai dan suara-suara yang gagal didengar.
Insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi
ojek online, memicu kemarahan publik. Ia tewas setelah terlindas kendaraan taktis
Brimob dalam kericuhan aksi. Peristiwa itu terekam dan tersebar luas di media
sosial, menggugah empati dan amarah. Protes menjalar ke Solo, Bandung, Mataram,
Makassar, dan kota-kota lainnya. Banyak yang berubah menjadi kerusuhan.
Fasilitas umum jadi sasaran.
Ironisnya, ini bukan kali pertama. Tahun 1998, 2019, 2020,
dan kini 2025, setiap letupan sosial besar selalu meninggalkan jejak di halte,
JPO, atau fasilitas umum lainnya. Pola ini terus berulang. Fasilitas publik
menjadi simbol frustasi dan ruang pelampiasan, serta cerminan rapuhnya relasi
antara negara dan warga. Bukan karena disanalah akar masalahnya, tetapi karena
hanya itu yang bisa dilihat, disentuh, dan dirusak.
Pertanyaannya kemudian muncul: mengapa fasilitas publik,
seperti halte dan jembatan penyeberangan, kerap menjadi sasaran dalam setiap
ledakan amarah sosial?
Halte: Wajah Negara yang Minim Penjagaan
Halte dan jembatan penyeberangan orang (JPO) adalah
representasi negara yang paling kasatmata—mudah dijangkau, tersebar di
jalan-jalan utama, tapi minim penjagaan. Tak seperti gedung pemerintah atau
markas kepolisian yang dilindungi ketat, halte berdiri tanpa pagar, tanpa pagar
kawat berduri, tanpa aparat bersenjata. Ketika kemarahan massa menggelegak,
halte jadi simbol yang paling mudah dimasuki, mudah dirusak, dan penuh makna.
Ia menjadi ruang paling dekat untuk menyalurkan kecewa yang tak tersampaikan.
Dalam psikologi sosial, kemarahan yang tidak dapat
dilampiaskan langsung kepada sasaran utama, kerap mencari pelampiasan yang
lebih dekat dan lebih lemah. Fasilitas umum seperti halte, jembatan
penyeberangan orang (JPO), atau gerbang tol menjadi “sasaran empuk” ketika
gedung DPR atau kantor kementerian tak terjangkau. Di tengah kerumunan yang
panas dan penuh emosi, simbol pelayanan publik bisa berubah menjadi objek
protes tanpa arah.
Dalam kerumunan besar, identitas personal memudar. Individu
merasa bebas dari tanggung jawab. Rasa aman karena “tidak dikenali”, mendorong
tindakan yang sulit dilakukan sendirian. Satu orang melempar batu, yang lain
mengikuti. Aksi menyebar seperti api. Tidak terencana, tidak terkendali. Norma
kelompok mendadak berubah: perusakan jadi tindakan bersama.
Tidak semua kerusuhan berasal dari demonstran. Dalam banyak
kasus, unsur luar menyusup untuk memperkeruh situasi. Provokator sengaja memicu
kekacauan demi membelokkan pesan aksi damai. Di sisi lain, kerusuhan ada dibuat
oleh kelompok penjarah yang memanfaatkan momen untuk menjarah di tengah
kekacauan. Tujuannya bukan aspirasi, tapi oportunisme.
Visual halte yang terbakar dan jembatan yang rusak
menciptakan kesan dramatis. Mudah viral, cepat menyebar. Sorotan media
meningkat, dan isu yang diperjuangkan—meski lewat cara negatif—menjadi
perbincangan publik. Bagi sebagian pihak, ini adalah “mencari publikasi lewat kerusakan”.
Cara cepat dan brutal untuk menyampaikan bahwa relasi antara negara dan
warganya sedang terganggu.
Halte harus kokoh dan berbasis komunitas
Halte harus kokoh dan berbasis komunitas—bukan sekadar
struktur fisik yang indah, tapi juga ruang publik yang kuat secara sosial dan
tangguh menghadapi risiko. Sebagian halte kita memang cantik, futuristik,
bahkan “Instagramable”. Namun secara teknis, mungkin memang belum disiapkan
untuk menghadapi risiko kerusuhan. Bahan kaca, akrilik, dan komponen elektronik
rentan dirusak. Tidak butuh alat berat untuk menghancurkannya. Karena itu,
perlu evaluasi serius terhadap desain halte dan fasilitas publik lainnya.
Infrastruktur kota tidak hanya perlu indah, tapi juga tangguh menghadapi
situasi darurat.
Solusinya bukan sekadar mengganti kaca dengan besi. Halte
bisa didesain modular—mudah diganti, tahan api, dan anti-vandal. Kamera
pengawas tersembunyi, pengamanan berbasis komunitas, serta keterlibatan warga
sekitar sangat penting. Ketahanan bukan hanya urusan material, tapi juga urusan
relasi sosial. Ketika warga merasa memiliki, mereka juga akan menjaga.
Bayangkan jika halte dijaga oleh warga sekitar—pengemudi
ojek, pedagang, pelajar, hingga satpam komplek. Dari kebersamaan itu bisa lahir
komunitas sederhana yang peduli dan aktif merawat halte. Sebut saja, “Sahabat
Halte”. Mereka bisa menggelar mural bersama, pameran karya anak-anak,
pertunjukan puisi, atau aksi bersih-bersih rutin. Seperti mushola kampung yang
dijaga bersama, halte pun bisa menjadi ruang hidup bersama. Pemerintah hanya
perlu menginisiasi dan memfasilitasi, selebihnya biarkan warga yang menghidupkannya.
Halte Kita, Tanggung Jawab Kita
Halte bukan milik pemerintah semata. Ia milik semua—pekerja,
pelajar, ibu rumah tangga, hingga lansia. Merusaknya bukan sekadar soal
kerugian material, tetapi juga mencederai martabat kota: harga diri sebuah ruang
hidup bersama. Menjaganya berarti menjaga diri kita sendiri—karena halte adalah
titik temu harian kita, ruang tunggu yang menyatukan berbagai latar belakang.
Perusakan halte hanyalah gejala dari persoalan yang lebih
kompleks: ketimpangan sosial, kegagalan komunikasi, dan kerapuhan saluran
aspirasi. Solusinya tak cukup hanya membangun kembali struktur fisiknya. Kita
perlu memulihkan rasa percaya, memperkuat keterlibatan sosial, dan menjadikan
halte sebagai simbol kehadiran negara yang manusiawi. Kota yang berpihak pada
warganya dimulai dari halte yang kokoh—secara fisik, nilai sosial, dan
representatif.
Merawat halte adalah tanggung jawab kita bersama. Dari
halte, kita bisa mulai membangun ulang kepercayaan yang retak—antara warga,
ruang publik, dan negara.(***)