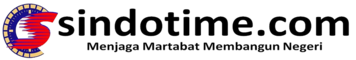Oleh : MUHAMMAD AKBAR
BAGI warga kota-kota besar di Indonesia—Jakarta, Bandung,
Surabaya, atau Medan—menyeberang jalan bukan lagi sekadar rutinitas biasa,
melainkan ujian nyali. Seharusnya, menyeberang adalah hak dasar: setiap orang
berhak bergerak bebas di ruang publik. Namun, di tengah padatnya lalu lintas
dan arus kendaraan yang nyaris tak pernah jeda, pejalan kaki justru seringkali
terpinggirkan. Yang semestinya mudah dan aman, malah berubah jadi momen
menegangkan, bahkan mengancam nyawa. Persoalannya bukan cuma rasa tidak nyaman,
melainkan juga keselamatan, waktu yang terbuang percuma, dan hak pejalan kaki
yang terus diabaikan.
Bagi pejalan kaki—apalagi lansia, anak-anak, ibu menggendong
balita, dan penyandang disabilitas—jalan raya sering kali terasa tidak ramah.
Justru sebaliknya, jalan menjadi arena adu deru mesin, klakson, dan kendaraan
yang melaju cepat. Seolah-olah, jalan hanya milik kendaraan bermotor. Padahal,
kota yang maju bukan diukur dari lebarnya jalan atau lancarnya lalu lintas,
melainkan dari seberapa aman dan nyaman warganya berjalan kaki dan menyeberang.
Lalu, mengapa menyeberang jalan di kota-kota besar bisa
sedemikian sulit? Apa yang salah dengan tata kelolanya? Apa yang bisa dilakukan
untuk membuatnya lebih aman dan nyaman?
Zebra Cross Hanya Pajangan, Nyali Tetap Jadi Andalan
Menyeberangi jalan di kota besar nyaris seperti menantang
maut. Zebra cross memang ada, tapi jangan harap pengendara bakal patuh. Masih
saja pada ngebut, bahkan ketika ada pejalan kaki yang sudah berada di atas
garis penyeberangan. Ironisnya lagi, banyak zebra cross justru berada di
titik-titik yang tidak strategis, jauh dari halte, dari pusat keramaian, atau
jalur pejalan kaki yang aktif digunakan.
Jembatan penyeberangan pun kerap terlalu tinggi dan tidak
ramah bagi lansia atau penyandang disabilitas. Tak sedikit pula yang dibiarkan
kusam, sempit, bahkan tidak terawat kayak bangunan terlantar. Alhasil, jembatan
yang harusnya jadi solusi malah berubah jadi rintangan. Maka, jangan heran bila
banyak orang akhirnya memilih “potong kompas”, nekat menyeberang langsung di
tengah jalan. Bukan karena tak tahu risiko, tapi karena itulah opsi paling
masuk akal di tengah tata kota yang tak berpihak pada pejalan kaki.
Di beberapa lokasi, tidak ada fasilitas penyeberangan sama
sekali, memaksa orang untuk mencari celah di antara arus kendaraan yang melaju
cepat. Akibatnya, pejalan kaki terpaksa “bernegosiasi” dengan arus kendaraan
yang tak pernah jeda, mereka harus gesit menengok kanan-kiri dengan was-was,
lalu buru-buru berlari kecil sambil berharap pengemudi melambat. Praktik ini
tak hanya melelahkan dan berbahaya, tetapi juga menunjukkan kegagalan kota
dalam menyediakan ruang publik yang aman dan ramah bagi semua warganya.
Menyeberang jalan pun akhirnya lebih mengandalkan nyali dan refleks, bukan
sistem kota yang semestinya menjamin keselamatan.
Lalu Lintas Kita Maju Kendaraannya, Tertinggal Budayanya
Fenomena ini jadi cermin betapa budaya berlalu lintas kita
belum berpihak pada pejalan kaki. Di banyak negara maju, mobil otomatis
melambat atau berhenti begitu melihat ada orang berdiri di zebra cross. Di
sini, yang terjadi justru sebaliknya: klakson dibunyikan sebagai peringatan
agar pejalan kaki minggir. Bahkan tak sedikit, pengemudi malah menambah
kecepatan saat melihat ada yang hendak menyeberang. Zebra cross seolah
kehilangan makna, sekadar hiasan aspal, dan pejalan kaki diperlakukan seperti
pengganggu arus lalu lintas. Situasi ini menunjukkan betapa minimnya empati,
rendahnya penghormatan terhadap hak pejalan kaki, dan absennya budaya berbagi
ruang yang adil di jalan.
Budaya pengemudi yang abai terhadap hak pejalan kaki tidak
lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari kelalaian sistemik yang sudah berlangsung
lama— dari regulasi yang lemah, pendidikan yang setengah hati, hingga praktik
harian yang terus dibiarkan. hingga praktik sehari-hari di lapangan. Dalam
ujian surat ijin mengemudi (SIM), nyaris tidak ada materi yang menekankan
pentingnya menghormati hak pejalan kaki, apalagi kewajiban berhenti di zebra
cross. Sekolah mengemudi pun lebih banyak fokus pada soal teknis, seperti cara
gas-rem, cara parkir atau mengoperasikan setir, ketimbang menanamkan etika
berkendara yang menghargai sesama pengguna jalan. Polisi lalu lintas? Jarang
menindak tegas pelanggaran di zebra cross. Lebih jauh lagi, banyak orang
belajar menyetir dari orang tua atau teman yang justru mewariskan kebiasaan
lama—kebiasaan yang tak pernah menganggap pejalan kaki sebagai prioritas di
jalan raya.
Ketimpangan Budaya Antar Negara
Banyak turis asing dibuat kaget ketika mencoba menyeberang
jalan di Indonesia. Mereka datang dengan asumsi bahwa zebra cross memiliki
kekuatan hukum dan moral. Jadi, mereka berdiri di tepi jalan, yakin kendaraan
akan berhenti. Tapi kenyataan berkata lain: nyaris tak ada kendaraan yang
peduli. Tidak sedikit yang nyaris tertabrak karena keliru memahami “budaya lalu
lintas” lokal. Di Indonesia, zebra cross lebih sering jadi dekorasi jalan
ketimbang penanda hak pejalan kaki.
Lucunya, saat orang Indonesia bepergian ke negara seperti Jepang,
Jerman, atau Australia, justru mereka yang bingung ketika mobil-mobil berhenti
memberi jalan. Alih-alih langsung nyebrang, malah bengong, ragu-ragu,
kikuk—karena terbiasa di Indonesia harus “mengalah” dan menunggu kendaraan
lewat. Padahal di sana, pengemudi malah kesal, karena pejalan kaki terlalu lama
menunda langkah. Ini bukan soal siapa yang salah atau benar, tapi menunjukkan
betapa jauhnya jurang budaya berlalu lintas kita dibanding negara-negara yang
lebih menghargai hak pejalan kaki.
Desain Kota: Megah untuk Kendaraan, Bahaya untuk Pejalan
Sulitnya menyeberangi jalan juga memperlihatkan betapa
desain kota-kota kita masih mengabaikan keberadaan pejalan kaki. Jalan terus
diperlebar, flyover dibangun, tapi semua itu umumnya hanya demi kelancaran kendaraan
bermotor. Sementara kebutuhan dasar warga untuk berjalan dengan aman dan nyaman
justru terpinggirkan. Trotoar sempit, tak ada ruang aman di tengah jalan untuk
berpijak, dan zebra cross yang tak terhubung dengan halte atau stasiun angkutan
umum—semua itu menandakan betapa rendahnya prioritas kota terhadap pejalan
kaki.
Mau ngajak orang naik transportasi umum? Mulailah dari
mempermudah akses pejalan kaki —termasuk kemudahan menyeberang jalan. Sebab
kalau untuk mencapai halte atau stasiun saja orang harus bertaruh nyawa, jangan
heran kalau minat naik angkutan umum tetap rendah.
Kota-kota seperti Seoul, Paris, atau Bogota, telah lama
menyadari bahwa mengutamakan kendaraan pribadi justru memperburuk kualitas
hidup. Mereka mulai merebut kembali ruang jalan untuk pejalan kaki dan
pesepeda, membangun budaya toleransi di lalu lintas, dan perlahan menggeser
prioritas: dari kecepatan kendaraan ke keselamatan warga. Hasilnya? Kota lebih
manusiawi, macet berkurang, warganya pun happy.
Solusi Nyata Menuju Kota Ramah Pejalan Kaki
Untuk memperbaiki situasi ini, berikut sejumlah langkah
konkret yang bisa dilakukan berikut ini.
Pertama, Revitalisasi fasilitas penyeberangan harus jadi
prioritas. Mulai dari menambah zebra cross di titik-titik strategis,
memperbaiki pencahayaan di malam hari, hingga memasang pelican crossing
otomatis, dan membenahi jembatan penyeberangan orang (JPO) agar ramah bagi
lansia (lanjut usia) serta penyandang disabilitas. Rambu dan marka harus jelas
dan mudah dipahami. Di sejumlah kota dunia bahkan sudah memakai lampu
penyeberangan adaptif berbasis sensor atau AI yang bisa menyesuaikan durasi
nyala lampu berdasarkan jumlah pejalan kaki. Teknologi ini bukan hanya
mengurangi waktu tunggu, tapi juga meningkatkan keselamatan secara signifikan.
Kedua, Materi ujian SIM dan kurikulum sekolah mengemudi
perlu segera direvisi. Edukasi tentang hak pejalan kaki harus dimasukkan
sebagai bagian penting, agar pengemudi tak hanya piawai mengendalikan
kendaraan, tapi juga paham etika berbagi jalan. Pengemudi perlu paham, bahwa
menghormati pejalan kaki adalah kewajiban hukum sekaligus cerminan budaya
berlalu lintas yang beradab.
Ketiga, Penegakan hukum harus tegas dan konsisten. Pengemudi
yang tidak memberi prioritas kepada pejalan kaki di zebra cross harus ditilang
tanpa pandang bulu. Selama aturan hanya jadi hiasan tanpa sanksi nyata,
pelanggaran akan terus dianggap biasa.
Keempat, Kampanye budaya lalu lintas harus digencarkan,
bukan hanya seremonial. Libatkan media, sekolah, hingga komunitas untuk
menanamkan empati di jalan raya—terutama soal pentingnya menghormati hak
pejalan kaki. Karena budaya berkendara yang beradab tidak lahir dari aturan
semata, tapi dari kesadaran bersama.
Kelima, Desain kota harus dirombak dengan orientasi pada
manusia, bukan semata kendaraan. Prinsip walkable city harus diterapkan, dengan
integrasi antara moda transportasi dan ruang pedestrian. Prioritas pembangunan
tak lagi bisa hanya berdasarkan kecepatan mobil, tapi pada kenyamanan dan
keselamatan warganya saat berjalan kaki.
Waktunya Memanusiakan Jalan
Menyeberangi jalan tidak seharusnya menjadi adu nyali. Ia
mencerminkan seberapa beradab sebuah kota memperlakukan warganya. Mobilitas
bukan cuma soal kendaraan bermotor, tapi tentang bagaimana setiap
orang—termasuk anak-anak dan lansia—bisa berpindah tempat dengan aman dan
nyaman. Kalau kita bisa bangga dengan jalan layang dan jembatan megah, tapi
seorang anak masih takut melangkah di zebra cross, maka kota ini belum
benar-benar layak huni.
Kota yang baik adalah kota yang memanusiakan jalan. Bukan
sekadar membanggakan tol layang atau flyover megah, tapi yang menghadirkan rasa
aman bagi seorang nenek yang menyeberang, anak kecil yang berjalan ke sekolah,
atau penyandang disabilitas yang menuju halte. Ukuran kemajuan kota bukan kecepatan
kendaraan, tapi seberapa layak dan aman ruang publiknya untuk semua warganya.
Sudah waktunya kota-kota kita berpihak pada manusia. Jalan
bukan milik eksklusif mereka yang berkendara. Jalan adalah ruang bersama. Dan
menyeberang jalan bukan seharusnya jadi ujian nyali, tapi hak dasar yang
dijamin oleh kota yang beradab.(***)