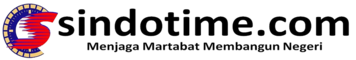HASIL : Dr. M.A. Dalmenda, S.Sos, M.Si menerima tanda lulus dengan yudisium Sangat Memuaskan dari Dekan Fikom Unpad merangkap tim promotor.
Bandung, Sindotime-Kamis, tepatnya pada 13 Februari 2025,
boleh dikatakan menjadi kenangan yang tidak akan bisa dilupakan oleh M.A
Dalmenda. Ya, di mana pada saat itu, Dosen Komunikasi Fisipol Unand Padang tersebut
resmi menyandang gelar Doktor. Ini setelah menyelesaikan pendidikan S3 di Pasca
Sarjana Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.
Kepastian ini setelah Sekretaris Magister (S2) Ilmu
Komunikasi Unand tersebut berhasil meyakinkan tim penguji yang terdiri dari
Ketua Sidang Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si, Sekretaris Sidang Promosi Doktor Dr.
Dadang Sugiana, M.Si serta Representasi Guru Besar Prof. Dr. Dian Wardiana
Sjuchro, M.Si dalam sidang terbuka promosi doktor.
Dengan tim Promotor yakni Prof. Dr. Engkus Kuswarno, MS, Dr.
Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos, SH, M.Si,
Dr. Emeraldy Chatra, M.I.Kom serta Opponent yang terdiri dari Prof. Dr.
Eni Maryani, M.Si, Prof. Dr. Suwandi, Sumartias, M.Si, Dr. Tine Silvana R,
M.Si.
”Alhamdulillah, ini semua berkat dukungan keluarga, teman
dan rekan-rekan, terutama rektor Unand sehingga saya berhasil menyelesaikan S3
ini,” ujar Dr. M.A. Dalmenda, S.Sos, M.Si yang juga Staff Ahli Rektor Unand
Bidang Komunikasi dan Media tersebut.
DIBACAKAN: Dr. M.A. Dalmenda, S.Sos, M.Si mendengarkan pembacaan hasil keputusan Sidang Promosi Doktor Bidang Komunikasi oleh Ketua Sidang Prof.Dr. Atwar Bajari, M.Si.
Pada sidang program doktor tersebut, Kepala Labor Film dan
TV Fisip Unand tersebut mengangkat disertasi KOMUNIKASI POLITIK DAN BUDAYA
PEMANGKU ADAT SUKU DI MINANGKABAU (Studi Etnografi Kritis Tentang Dominasi
Pemangku Adat dalam Proses Demokrasi di Sumatera Barat).
Penelitian ini mengkaji dinamika komunikasi politik dan
peran budaya pemimpin tradisional di Nagari Kubung Tigo Baleh, Kabupaten Solok,
Sumatera Barat, yang mencerminkan kompleksitas interaksi antara nilai-nilai
tradisional dan demokrasi modern. Politisasi pemimpin tradisional telah secara
fundamental mengubah pola komunikasi dan proses pengambilan keputusan di
tingkat nagari, di mana legitimasi kultural sering dimanfaatkan untuk dukungan
politik. Forum-forum tradisional, yang seharusnya menjadi tempat musyawarah
mufakat, telah bertransformasi menjadi arena konsolidasi politik, menciptakan
ketegangan antara peran pemimpin tradisional sebagai penjaga nilai-nilai budaya
dan keterlibatan mereka dalam politik praktis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
etnografi kritis dan paradigma konstruktivisme, dengan fokus pada tiga aspek
utama: pola komunikasi politik, identifikasi nilai-nilai budaya Minangkabau,
dan konflik yang muncul antara otoritas tradisional dan sistem demokrasi
modern. Temuan menunjukkan bahwa keterkaitan antara adat dan hukum Islam secara
signifikan mempengaruhi komunikasi politik, yang memerlukan reformasi dalam
kepemimpinan tradisional untuk memastikan peran yang efektif dalam konteks
kontemporer sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kohesi
sosial.
Di mana, latar belakangnya adalah komunikasi politik dan
budaya pemangku adat suku Minangkabau, terutama di daerah Kubuang Tigo Baleh,
terdapat dinamika yang kompleks antara tradisi dan modernitas. Teori
konstruktivisme, seperti yang dijelaskan oleh Peter L. Berger, dapat digunakan
untuk memahami bagaimana identitas dan struktur sosial dibentuk melalui
interaksi sosial dan pengalaman kolektif masyarakat. Dalam hal ini, pemangku
adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai aktor
yang terlibat dalam proses demokrasi yang lebih luas, di mana nilai-nilai adat
dan norma-norma politik saling berinteraksi dan membentuk satu sama lain (Roza
& B.S, 2022; Afdhal, 2023).
Kubuang Tigo Baleh, sebagai bagian dari Luhak Tanah Datar,
memiliki sejarah yang kaya dan struktur sosial yang unik. Nagari di
Minangkabau, termasuk Kubuang Tigo Baleh, memiliki sistem pemerintahan yang
berbasis pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Pemimpin adat, atau ninik
mamak, dipilih melalui musyawarah dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni
sosial serta menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini
mencerminkan prinsip “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
yang menjadi landasan bagi masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupan
sosial dan politik mereka (Rahmasari et al., 2023; Kosasih, 2014). Namun, dalam
perkembangan politik modern, pemangku adat di Minangkabau menghadapi tantangan
baru ketika banyak dari mereka terlibat dalam politik praktis.
PAPARAN: Dr. M.A. Dalmenda, S.Sos saat promovendus mempertanggungjawabkan Disertasi dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Bidang Komunikasi.
Keterlibatan ini sering kali menimbulkan konflik kepentingan
antara peran mereka sebagai penjaga nilai-nilai adat dan tuntutan politik yang
harus mereka penuhi. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam fungsi
pemangku adat, di mana mereka tidak hanya berperan sebagai mediator dalam
konflik sosial, tetapi juga sebagai politisi yang harus mempertimbangkan
kepentingan politik mereka sendiri (Afdhal, 2023; Andoni & Eros, 2019).
Dalam konteks ini, teori konstruktivisme membantu kita memahami bagaimana
identitas pemangku adat dan masyarakat Minangkabau terbentuk melalui interaksi
dan negosiasi antara tradisi dan modernitas (Roza & B.S, 2022; Afdhal,
2023).
Dinamika ini juga terlihat dalam cara masyarakat Minangkabau
merespons perubahan yang terjadi. Masyarakat tidak hanya menerima perubahan,
tetapi juga beradaptasi dan mengintegrasikan nilai-nilai baru ke dalam struktur
sosial mereka. Misalnya, meskipun ada pergeseran dalam peran pemangku adat,
nilai-nilai demokrasi yang telah tertanam dalam budaya Minangkabau tetap
menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Proses musyawarah dan mufakat tetap
menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, meskipun dalam konteks yang
lebih kompleks (Rahmasari et al., 2023; Afdhal, 2023).
Dengan demikian, pemahaman tentang komunikasi politik dan
budaya di Kubuang Tigo Baleh harus mempertimbangkan interaksi antara tradisi
dan modernitas, serta bagaimana kedua elemen ini saling membentuk dalam konteks
sosial yang lebih luas (Roza & B.S, 2022; Afdhal, 2023). Dalam
kesimpulannya, peran pemangku adat di Minangkabau, khususnya di Kubuang Tigo
Baleh, mencerminkan kompleksitas hubungan antara budaya, politik, dan
identitas. Teori konstruktivisme memberikan kerangka kerja yang berguna untuk
memahami bagaimana nilai-nilai adat dan praktik politik saling berinteraksi dan
membentuk struktur sosial. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat lebih
menghargai bagaimana masyarakat Minangkabau beradaptasi dengan perubahan sambil
tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya mereka (Roza & B.S,
2022; Afdhal, 2023).
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji
dinamika komunikasi politik dan budaya pemangku adat di Nagari Kubung Tigo
Baleh, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan fokus pada interaksi antara
sistem nilai tradisional dan praktik demokrasi modern. Dalam konteks ini,
komunikasi menjadi elemen fundamental dalam pelaksanaan fungsi adat di kalangan
kaum dan suku di Minangkabau. Gaya komunikasi yang digunakan oleh penghulu
adat, seperti yang diungkapkan melalui konsep “kato manurun,”
mencerminkan posisi superior penghulu dalam struktur sosial, di mana mereka
berperan sebagai sumber nasihat dan bimbingan bagi anak kemenakan.
Namun, dominasi kekuasaan yang melekat pada pemangku adat tidak
dapat dipandang sebagai hal yang tabu, melainkan sebagai bagian dari eksistensi
kelompok adat yang memiliki otoritas di daerah mereka. Dalam praktiknya,
meskipun pemangku adat terlibat dalam musyawarah untuk mufakat, terdapat
kalanya keputusan tidak tercapai, yang dapat mengganggu proses demokrasi di
nagari. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi pertanyaan mengenai
mengapa dominasi kekuasaan dalam komunikasi politik oleh pemangku adat terjadi,
serta implikasi yang ditimbulkan dalam konteks demokrasi deliberatif yang
diterapkan oleh masyarakat Minangkabau.
AKRAB: Dr. M.A. Dalmenda, S.Sos,Foto bareng Istri Apt.Lili Iswari,S.Si diapit Dekan Fisip Unand, Dr Jendrius M.Si dan Dr.Yuliandre Darwis. Ph.D, mantan Ketua KPI Pusat.
Tujuan penelitian ini mencakup analisis pola komunikasi
politik pemangku adat dalam konteks demokrasi lokal, identifikasi nilai-nilai
dan identitas budaya yang tercermin dalam pola komunikasi tersebut, serta
deskripsi konflik yang muncul antara otoritas pemangku adat dan sistem
demokrasi modern dalam pengambilan keputusan politik. Dengan pendekatan
kualitatif dan metode etnografi kritis, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana dominasi pemangku adat
mempengaruhi interaksi sosial dan politik di nagari. Selain itu, penelitian ini
juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan pemangku adat dalam
politik praktis dapat menyebabkan polarisasi di kalangan anak kemenakan dalam
kaum dan suku.
Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pengembangan ilmu
komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi politik dan budaya, serta
memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem kepemimpinan adat yang lebih
responsif terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang di masyarakat
Minangkabau..
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah
metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami bagaimana individu atau
komunitas menerima isu tertentu (McCusker & Gunaydin, 2015). Penelitian
kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan deskripsi yang kaya tentang
fenomena dan mendorong pemahaman yang lebih dalam mengenai substansi peristiwa
(Sofaer, 1999). Creswell (2007) mengidentifikasi karakteristik penelitian
kualitatif yang baik, termasuk penggunaan prosedur pengumpulan data yang tepat,
fokus penelitian yang jelas, dan analisis data yang mendalam. Proses penelitian
dimulai dengan pertanyaan penelitian yang menentukan metode pengumpulan dan
analisis data. Penelitian kualitatif bersifat dinamis, memungkinkan perubahan
dan penyesuaian selama analisis (Srivastava & Thomson, 2009). Mulyana
(2004) menekankan bahwa penelitian kualitatif memiliki perspektif subjektif,
dengan sembilan ciri yang mencakup sifat realitas yang kompleks, interaksi
sosial yang saling mempengaruhi, dan penekanan pada makna dan konteks.
Karakteristik Penelitian Kualitatif, Karakteristik utama
dari metode penelitian kualitatif meliputi penggunaan lingkungan alami sebagai
sumber data, sifat deskriptif analitik, fokus pada proses daripada hasil,
pendekatan induktif, dan penekanan pada makna. Penelitian kualitatif
mengandalkan pengamatan langsung dan interaksi dengan partisipan untuk memahami
fenomena sosial dalam konteks yang spesifik. Data yang dikumpulkan bersifat
naratif dan tidak terukur dalam angka, memungkinkan peneliti untuk menggali
makna di balik peristiwa yang terjadi. Penelitian ini juga mengutamakan
pemahaman terhadap perspektif partisipan, di mana peneliti berperan sebagai
instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2005). Dengan
demikian, penelitian kualitatif berusaha untuk memberikan gambaran yang
mendalam dan holistik tentang fenomena yang diteliti, tanpa mengabaikan konteks
sosial dan budaya yang melingkupinya.
Penelitian ini berfokus pada pendekatan etnografi kritis
untuk mengkaji fenomena dominasi kekuasaan pemangku adat dalam konteks politik
di Minangkabau, dengan tujuan untuk mengungkap relasi kekuasaan yang
tersembunyi dan struktur dominasi dalam masyarakat. Etnografi kritis dipilih
karena kemampuannya untuk tidak hanya mendeskripsikan realitas sosial, tetapi
juga untuk menganalisis interaksi antara kekuasaan tradisional pemangku adat
dan sistem politik modern, serta dampaknya terhadap dinamika sosial di tingkat
kaum, suku, dan nagari. Sumber data penelitian mencakup para pemangku adat yang
terlibat dalam politik praktis, seperti pengurus partai dan pejabat politik,
serta akademisi dan pengamat budaya Minangkabau.
Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam,
observasi partisipan, dan analisis dokumen, dengan penekanan pada kolaborasi
aktif antara peneliti dan partisipan untuk mendorong perubahan sosial yang
lebih adil. Validasi data dilakukan melalui pengamatan yang teliti,
triangulasi, dan pengecekan dengan rekan-rekan akademis. Penelitian ini
dilaksanakan di nagari-nagari dalam Nagari Kubuang Tigo Baleh, Kabupaten Solok,
yang terletak sekitar 55 kilometer dari Kota Padang, sebagai bagian dari upaya
untuk memahami dan mengadvokasi ketimpangan serta dominasi yang terjadi dalam
masyarakat adat Minangkabau.
DUKUNGAN: Dr. M.A. Dalmenda, S.Sos, bersama Dekan Fisip Unand Dr. Jendrius, M.Si, Dr. Yuliandre Darwis, Ph.D mantan Ketua KPI Pusat, Wakil Ketua Gebu Minang Pusat Irjen Pol (Purn) Drs. H. Marwan Paris, M.BA. Dt.Maruhun Saripado beserta istri Er, dan Tokoh Solok di Jawa Barat Dr. Abdul Rivai, SP.A Dt. Rajo Batuah beserta istri Jus.
Sejumlah item yang menjadi pembahasan dalam disertasi ini
adalah, Pola Komunikasi Budaya Minangkabau. Di mana pola komunikasi dalam
budaya Minangkabau dipengaruhi oleh interaksi antara adat dan syariat Islam,
dengan prinsip “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
sebagai landasan dalam pengambilan keputusan sosial dan politik. Pemangku adat
berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, menjaga
keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam era reformasi. Meskipun pola
komunikasi dalam masyarakat Minangkabau pada dasarnya bersifat kolektif dengan
keputusan yang diambil melalui musyawarah dan mufakat, terdapat pergeseran
menuju pola komunikasi yang lebih instruktif. Dalam pola ini, pemangku adat
cenderung memberikan arahan langsung terkait pilihan politik kepada anak
kemenakan tanpa membuka ruang dialog yang setara, yang mengakibatkan erosi
prinsip demokrasi deliberatif dan membatasi ruang aspirasi politik anak
kemenakan.
Sistem patron-klien dalam budaya Minangkabau, yang dikenal
sebagai “Orang Dalam” atau “Induak Samang,” menggambarkan
hubungan kompleks antara pemangku adat sebagai patron dan anak kemenakan
sebagai klien. Hubungan ini menciptakan ketergantungan sosial dan ekonomi, di
mana patron diharapkan memberikan dukungan kepada klien, sementara klien
memberikan loyalitas kepada patron. Namun, meningkatnya kesadaran masyarakat
akan hak-hak mereka telah mendorong klien untuk menuntut partisipasi yang lebih
besar dalam pengambilan keputusan. Komunikasi di lapau-lapau atau warung kopi
menjadi ruang publik yang penting untuk interaksi sosial dan diskusi politik,
di mana pemangku adat dapat mempengaruhi opini publik dan membangun kesadaran
politik di kalangan masyarakat, meskipun hal ini juga dapat menciptakan
ketegangan dalam hubungan patron-klien tradisional.
Kemudian nilai-nilai adat dan budaya. Di mana sistem
kepemimpinan adat di Minangkabau mengalami transformasi signifikan sebagai
respons terhadap modernisasi, di mana para pemangku adat menjalankan peran
ganda sebagai penjaga warisan budaya dan pemimpin yang harus beradaptasi dengan
sistem pemerintahan modern. Dalam menjalankan fungsinya, mereka tidak hanya
memimpin musyawarah adat dan menyelesaikan masalah masyarakat secara
tradisional, tetapi juga dituntut untuk menguasai teknologi dan sistem
administrasi kontemporer. Proses adaptasi ini membawa dampak besar terhadap
cara pemangku adat menjalankan perannya, di mana mereka harus mampu
mengintegrasikan diri ke dalam struktur birokrasi formal sambil tetap
mempertahankan legitimasi tradisional. Tantangan ini semakin kompleks dengan
hadirnya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih akuntabel, meskipun
juga membuka peluang bagi pemangku adat untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai
kepemimpinan tradisional tetap relevan dalam konteks modern.
BANGGA: Dr. M.A. Dalmenda, S.Sos Bareng para Alumnus Angkatan 91 SMANSA Solok Cabang Bandung.
Dalam menghadapi tantangan modernisasi, pemangku adat
Minangkabau mengembangkan pendekatan adaptif yang memungkinkan mereka
mempertahankan esensi kepemimpinan tradisional sambil mengadopsi
praktik-praktik modern. Proses ini mencakup transformasi dalam cara
berkomunikasi, mengelola konflik, dan pengambilan keputusan. Mereka kini
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan dan
menyebarkan informasi, serta mengadopsi metode manajemen modern dalam
pengelolaan sumber daya komunal.
Legitimasi kepemimpinan tradisional mengalami pergeseran, di
mana otoritas tidak hanya bersumber dari warisan adat, tetapi juga dari
kapasitas dalam menangani isu-isu kontemporer. Filosofi “Adat Basandi
Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” tetap menjadi landasan penting dalam
interaksi antara nilai-nilai tradisional, agama, dan praktik demokrasi modern,
yang membentuk pola komunikasi dan pengambilan keputusan para pemangku adat.
Dalam konteks ini, pemangku adat dituntut untuk membuktikan relevansi
kepemimpinan mereka dengan memberikan solusi terhadap permasalahan modern, yang
menciptakan kebutuhan akan pengembangan kompetensi baru dalam kebijakan publik
dan manajemen organisasi.
Konflik Dalam Komunikasi Politik Minangkabau. Yakni
komunikasi politik di Minangkabau memiliki karakteristik unik yang berakar pada
sistem adat dan budaya matrilineal. Struktur kepemimpinan yang dikenal dengan
istilah tungku tigo sajarangan, yang melibatkan ninik mamak, alim ulama, dan
cadiak pandai, sering mengalami konflik ketika berhadapan dengan sistem politik
modern yang lebih hierarkis. Aspek eksternal seperti modernisasi dan penetrasi
teknologi informasi juga mempengaruhi dinamika komunikasi dan budaya di
Minangkabau. Media sosial dan platform digital membawa tantangan baru dalam
mempertahankan nilai-nilai tradisional, sementara praktik merantau menciptakan
interaksi dengan budaya luar yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai
lokal. Hal ini berpotensi menciptakan konflik antara generasi muda yang kembali
dengan pandangan baru dan kelompok tradisionalis yang ingin mempertahankan
adat.
SUPPORT: Dr. M.A. Dalmenda, S.Sos,mendapatkan ungkapan Selamat dan Sukses karangan bunga dari Rektor Unand Efa Yonnedi, Ph.D.
Konflik adat dalam masyarakat Minangkabau sering dipicu oleh
perbedaan interpretasi terhadap aturan adat yang diwariskan secara lisan dan
perebutan sumber daya alam seperti tanah ulayat. Ketidakjelasan dalam
penafsiran adat dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan
pribadi, sementara perubahan sosial budaya akibat modernisasi dan globalisasi
menciptakan ketegangan antara generasi tua dan muda. Penyelesaian konflik adat
memerlukan pendekatan holistik dan partisipatif, dengan melibatkan peran Bundo
Kanduang sebagai sosok sentral dalam struktur sosial Minangkabau. Sebagai
penjaga nilai-nilai adat dan moral, Bundo Kanduang harus mampu menjembatani
kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernisasi, sambil
menjaga netralitas dalam konflik politik. Upaya revitalisasi sistem
penyelesaian konflik adat yang melibatkan generasi muda dan memanfaatkan
teknologi modern menjadi kunci untuk memastikan solusi yang dihasilkan tetap
relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Minangkabau di era
globalisasi.
Komunikasi politik di Minangkabau memiliki karakteristik
unik yang berakar pada sistem adat dan budaya matrilineal. Struktur
kepemimpinan yang dikenal dengan istilah tungku tigo sajarangan, yang
melibatkan ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai, sering mengalami konflik
ketika berhadapan dengan sistem politik modern yang lebih hierarkis. Aspek
eksternal seperti modernisasi dan penetrasi teknologi informasi juga
mempengaruhi dinamika komunikasi dan budaya di Minangkabau. Media sosial dan
platform digital membawa tantangan baru dalam mempertahankan nilai-nilai
tradisional, sementara praktik merantau menciptakan interaksi dengan budaya
luar yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Hal ini berpotensi
menciptakan konflik antara generasi muda yang kembali dengan pandangan baru dan
kelompok tradisionalis yang ingin mempertahankan adat.
Konflik adat dalam masyarakat Minangkabau sering dipicu oleh
perbedaan interpretasi terhadap aturan adat yang diwariskan secara lisan dan
perebutan sumber daya alam seperti tanah ulayat. Ketidakjelasan dalam
penafsiran adat dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan
pribadi, sementara perubahan sosial budaya akibat modernisasi dan globalisasi
menciptakan ketegangan antara generasi tua dan muda. Penyelesaian konflik adat
memerlukan pendekatan holistik dan partisipatif, dengan melibatkan peran Bundo
Kanduang sebagai sosok sentral dalam struktur sosial Minangkabau. Sebagai
penjaga nilai-nilai adat dan moral, Bundo Kanduang harus mampu menjembatani
kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernisasi, sambil
menjaga netralitas dalam konflik politik. Upaya revitalisasi sistem
penyelesaian konflik adat yang melibatkan generasi muda dan memanfaatkan
teknologi modern menjadi kunci untuk memastikan solusi yang dihasilkan tetap
relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Minangkabau di era
globalisasi.
Sehingga di dapat kesimpulan 1) Pola Komunikasi Politik
Pemangku Adat. Pola komunikasi politik pemangku adat Minangkabau mengalami
transformasi fundamental dalam konteks demokrasi lokal, di mana otoritas
tradisional yang seharusnya berfungsi untuk membimbing anak kemenakan kini
lebih sering digunakan sebagai alat mobilisasi dukungan politik. Forum-forum
adat yang dulunya merupakan ruang musyawarah mufakat telah beralih menjadi
arena konsolidasi politik, yang berpotensi menciptakan ketegangan dalam relasi
mamak-kemenakan dan mengancam kohesivitas sosial masyarakat nagari. Erosi
kepercayaan terhadap kepemimpinan tradisional terjadi ketika pemangku adat
lebih mengutamakan agenda politik dibandingkan fungsi pembinaan, yang
berimplikasi pada efektivitas mereka dalam menjaga harmoni sosial.
Lalu, 2) Reinterpretasi Nilai dan Identitas Budaya.
Nilai-nilai dan identitas budaya Minangkabau, yang berlandaskan pada sistem
matrilineal dan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah,” mengalami reinterpretasi ketika berhadapan dengan kepentingan
politik praktis. Pemangku adat sering kali menggunakan simbol-simbol adat untuk
melegitimasi kepentingan politik mereka, yang menciptakan ambiguitas dalam
pemaknaan nilai-nilai tradisional. Pergeseran fokus dari perlindungan hak-hak
perempuan dan kelestarian harta pusaka kaum menuju aktivitas politik dapat
mengancam transmisi nilai-nilai adat kepada generasi muda, serta menciptakan
kesenjangan dalam pemahaman identitas kultural Minangkabau.
Kemudian, 3) Konflik dalam Komunikasi Politik. Konflik dalam
komunikasi politik di Minangkabau sering kali dipicu oleh perbedaan pandangan
dan kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat. Dinamika komunikasi
politik tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tetapi juga strategi
untuk membangun aliansi dan mengelola perbedaan. Ketegangan yang muncul dari
perdebatan mengenai legitimasi dan otoritas antara pemimpin adat dan pejabat
pemerintah dapat mengakibatkan konflik terbuka. Oleh karena itu, penting untuk
memahami konteks budaya Minangkabau dalam komunikasi politik guna
mengidentifikasi potensi konflik dan mencari solusi yang memfasilitasi dialog
dan rekonsiliasi.
Sejumlah saran dalam hal ini yakni 1. Penelitian Mendalam
tentang Transformasi Digital. Dianjurkan bagi peneliti selanjutnya untuk
melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak transformasi digital
terhadap komunikasi antara pemangku adat dan generasi muda. Penelitian ini
penting untuk memahami kesenjangan digital yang semakin melebar dan mengembangkan
model komunikasi politik yang mengintegrasikan platform digital dengan
nilai-nilai musyawarah mufakat. Selain itu, kajian tentang strategi
revitalisasi peran pemangku adat dalam era digital juga perlu dilakukan, dengan
fokus pada metode pembelajaran yang adaptif terhadap karakteristik generasi
milenial dan Gen-Z.
Kemudian, 2. Kajian Implikasi Politisasi Pemangku Adat.
Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang implikasi
politisasi pemangku adat terhadap sistem matrilineal dan struktur sosial
masyarakat Minangkabau. Mengingat sistem matrilineal merupakan pilar
fundamental dalam masyarakat Minangkabau, penting untuk mengembangkan model
tata kelola pemerintahan yang dapat mengakomodasi kearifan lokal dalam
administrasi modern. Penelitian ini juga harus diarahkan pada penguatan
kapasitas kelembagaan adat dalam menghadapi dinamika politik kontemporer,
termasuk pengembangan sistem kaderisasi pemangku adat yang memadukan
nilai-nilai tradisional dengan kompetensi modern.
Lalu, 3. Dialog Terbuka dan Mediasi dalam Penyelesaian
Konflik. Pemangku adat perlu mengimplementasikan dialog terbuka dan mediasi
sebagai metode penyelesaian konflik dalam komunikasi politik di Minangkabau.
Mereka harus berperan sebagai mediator yang mampu menjembatani perbedaan
pandangan di antara kelompok masyarakat. Dengan menciptakan forum diskusi yang
melibatkan semua pihak, pemangku adat dapat meredakan ketegangan dan mencari
solusi yang saling menguntungkan. Pelatihan dalam keterampilan mediasi dan
resolusi konflik juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemangku
adat dalam menangani permasalahan yang muncul di masyarakat.
SUKACITA: Dr. M.A. Dalmenda, S.Sos mendapatkan ungkapan Selamat dan Sukses dari Prof. Muhammad Zilal Hamzah,Ph.D Ketu Program Doktoral Kebijakan Publik IEF/ FEB Universitas Trisakti Jakarta.
Menariknya, sidang program doktor ini dihadiri langsung oleh
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Dr. Jendrius,
M.Si yang sentiasa mensupport dan memantau proses studi dirinya hingga
penyelesaian. Dr. Yuliandre Darwis, S.Sos, M.Mass.Comm, Ph.D, selaku mentor
yang membawa dirinya ke dunia akademisi, tepatnya di kampus Universitas
Andalas. Kemudian, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Marwan Paris Dt. Maruhun Saripado,
MBA, selaku Wakil Ketua Gebu Minang Pusat, dr. H. Abdul Rivai, Sp. A, Dt. Rajo
Batuah beserta istri, tokoh perantau Ranah Minang di Jawa Barat, rekan alumni
angkatan 91 Smansa Solok cabang Padang, Jabodetabek dan Bandung.
“Dan yang paling spesial adalah istri saya Apt. Lili Aswari,
S.Si yang penuh cinta memberikan dukungan tanpa henti dan perhatian yang tulus.
Dan merelakan saya tidur di Mushola kampus selama 15 hari tanpa jeda. Lalu
Putra pertama saya tercinta, Nabil Anjabi, yang selalu menjadi penyemangat papa
dalam menyelesaikan studi ini. Kedua kakak saya yang hadir, Asriyanti, A.Md dan
Selvianora, S.Pd, Keponakan saya yang hadir, Desi Masfianti, S.E, datang dari
Palembang,” katanya.
Sekadar diketahui, M.A. Dalmenda sendiri lahir pada 26 April
1972 di Kabupaten Solok. Beliau adalah seorang akademisi dan profesional di
bidang komunikasi. Ia merupakan anak dari Baharuddin Dt. Sati Garang dan
Agusti, serta menikah dengan Lili Iswari dan memiliki tiga anak: Nabil Anjabi,
Alfaruqi Anjabi, dan Fayrel Kenzie Anjabi. Dalmenda memulai pendidikan dasarnya
di SD Inpres Selayo pada tahun 1985, diikuti dengan pendidikan menengah di SMPN
1 Selayo (1988) dan SMA 1 Solok (1991). Ia melanjutkan pendidikan tinggi dengan
meraih gelar D3 dari Akademi Ilmu Komunikasi Padang (1994) dan S1 di bidang
Jurnalistik dari Fakultas Ilmu Komunikasi Usahid Jakarta (2001), pendidikan S3
dalam Komunikasi Politik di Universitas Padjadjaran.
Dalam karier profesionalnya, Dalmenda telah menjabat di
berbagai posisi penting, termasuk sebagai Kabag Humas Setdako Padang Panjang
(2014-2015), Produser di Antara TV LKBN Antara Biro Sumbar (2016), dan Dosen
Komunikasi di Fisipol Unand Padang (sejak 2015). Ia juga menjabat sebagai
Sekretaris Magister Ilmu Komunikasi Unand pada tahun 2017 dan diangkat kembali
pada tahun 2023, serta sebagai Kepala Labor Film dan TV Fisip Unand. Selain
itu, ia pernah menjabat sebagai Staff Ahli Rektor Unand di bidang Komunikasi
dan Media (2020-2022).
Dalmenda aktif dalam organisasi profesi dan sosial, menjadi
anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar dan menjabat sebagai
Penanggung Jawab Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI) Daerah Sumbar
sejak 2017. Pada tahun 2023, ia diangkat sebagai Kepala Biro Hak Sako dan
Pusako di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, menunjukkan
komitmennya terhadap pelestarian budaya.
Dalam dunia media, Dalmenda memiliki pengalaman luas sebagai
reporter di TVRI Sumbar, Padang TV, presenter di Triarga TV, dan penulis untuk
Harian Metro Andalas. Selain itu, ia juga aktif sebagai penyair dan seniman di
Taman Budaya Sumatera Barat, sering menjuarai lomba penulisan antologi puisi
tingkat nasional.(*/zoe)